Lihat saja kecenderungan kita, baik sebelum maupun sesudah Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak, Rabu, 17 April 2019 lalu. Situasi sebelum Pemilu begitu hiruk-pikuk. Dudi (dunia digital) atau Dumes (dunia media sosial), begitu panas membara. Saling hujat, saling hina, saling caci, saling maki, saling tuding, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, terus-terusan mewarnai dunia maya itu. Fragmentasi terjadi antara dua kubu pasang calon; 01 dan 02. Di dunia nyata pun kiranya tak jauh berbeda.
Hingga beberapa hari usai hajatan demokrasi terbesar di dunia itu, faktanya suasana kebatinan mereka belum benar-benar move on dan tidak serta-merta mendingin. Masih saja muncul saling curiga satu dengan lainnya. Juga masih saling praduga antar sesama. Hujatan, cacian, makian, dll, rupanya tidak hilang seiring usainya pencoblosan, terutama di dunia media sosial. Lebih buruk lagi, jika suasana ini dikipasi atau dikompori oleh (mereka yang dinilai sebagai) tokoh agama atau tokoh masyarakat.
Ujung-ujungnya, untuk membela kepentingan politik, kita tak sungkan dan tak canggung menyeret-nyeret terma agama. Pendukung si Anu “kafir”, “fasik”, tak pakai akal, atau cap buruk lainnya. Bahkan beberapa diantaranya hingga tega menerakakan saudara muslimnya sendiri, hanya karena pilihan yang tak sama. Surga, lalu, dikapling-kapling oleh pendukung calon tertentu dan “haram” untuk pendukung calon yang lain. Alasan keagamaan untuk membenarkan pilihan politik pun dianggap absah.
Ayat-ayat dan Hadis-hadis juga ramai bertebaran. Dipolitisasi untuk menguatkan kepentingan politik tertentu. Tak peduli, apakah penerapannya sesuai konteks atau justru menyalahinya. Asalkan sesuai selera, doktrin agama itu dipakainya tanpa perasaan berdosa. Padahal semestinya, kita hati-hati menerapkan ayat atau Hadis. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa menafsirkan al-Quran dengan rayunya, maka bersiap-siaplah menempati tempat di neraka.” (HR. al-Tirmidzi). Ray identik dengan kepentingan hawa nafsu atau selera yang pragmatis.
Karenanya, semestinya kita (umat Islam) ingat betul, bahwa politik itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan tema besar agama. Dan, ia semata wasilah (perantara) mencapai kemaslahatan bersama. Dalam sejarahnya, berdasarkan Hadis-hadis yang valid, diantaranya riwayat Ahmad bin Hanbal, Rasulullah Saw diutus li utammima shalih al-akhlaq (untuk kebaikan moralitas), bukan untuk merebut kekuasaan. Hakikat bitsah beliau bukan untuk menegakkan politik.
Keluhuran akhlak tentu saja jauh di atas kepentingan politik. Akhlak haruslah menjadi pengontrol politik. Para politisi, jika ingin mulia dunia akhirat, berjalanlah di atas rel akhlak. Jangan sampai, untuk meraih simpati atau dukungan supaya meraih kemenangan, akhlak lalu dilabrak dan diabaikan begitu saja. Nilai agama lalu dicampakkan seakan tiada guna dan makna. Ketika menjadi penguasa, juga jadilah penguasa yang senantiasa berjalan di atas rel akhlak, sehingga kebijakannya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat.
Pun kita para pendukung/simpatisan, jika ingin luhur dunia akhirat, dukunglah jagoan kita dengan landasan akhlak mulia. Akhlak akan melahirkan peradaban yang madani (cosmopolitan) dan penuh penghargaan pada keragaman. Sikapi perbedaan dengan keluhuran. Di situlah, agama memainkan perannya. Berpolitiknya dengan landasan agama, bukan beragama dengan landas politik.
Dalam beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Prof. Harun Nasution (Mantan Rektor IAIN Syahid Jakarta), disebutkan bahwa sengketa teologi berawal dari sengketa politik. Perpecahan umat Islam sejak zaman Abu Bakar al-Shiddiq dan memuncak pada masa Khalifah Keempat, Ali bin Abi Thalib, itu dilatari persoalan kekuasaan atau politik. Kala itu, sikap Ali yang menyetujui tahkim atau arbitrase dengan Muawiyah, direspon beragam oleh kaum muslim.
Sebagian keluar dari barisan Ali. Mereka lalu disebut Khawarij, yang memiliki karakter garang dan keras. Sebagian abstain alias tidak berpihak pada siapapun. Mereka inilah Murjiah, yang menyerahkan segala urusan pada Allah Swt. Mereka kelompok yang cenderung adem-ayem. Juga ada sebagian yang setia pada Ali dan sebagiannya cenderung fanatik berlebihan. Mereka inilah kelompok Syiah.
Dari persoalan politik kekuasaan itu, yang terjadi sejak zaman Abu Bakar, diantara efek buruknya adalah terbunuhnya Umar bin al-Khaththab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka pemimpin terbaik yang dimiliki umat Islam. Ketakwaan dan keadilannya tidak diragukan. Namun berhadapan dengan kepentingan politik, nyatanya mereka tak berdaya. Berbagai persoalan politik setelahnya lalu berkembang liar.
Inilah ruginya jika akhlak tidak menjadi darah yang mengiringi hiruk-pikuk politik kekuasaan. Seyogyanya, kita mampu menjadikan sejarah suram ini sebagai pengalaman mahal, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan penuh keluhuran. Pelajaran telah dihamparkan. Hanya bijak bestari yang mampu mengambil mutiara-mutiara itu.
Pertanyaannya kini: pelajaran apa yang semestinya kita petik dari fakta sejarah kelam umat Islam dan hajatan demokrasi 2019 yang baru saja usai diselenggarakan?
Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara besar, yang diperjuangkan oleh semua kalangan. Ia berdiri di atas keragaman suku, agama, ras dan golongan. Tak heran, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi mantra sakti di Negeri Zamrud Katulistiwa ini. Ini juga menunjukkan, keragaman di negeri ini adalah fitrah yang tak mungkin dipungkiri. Menjaga keragaman dengan penuh keriangan, akan menjadikan negeri ini kian besar dan penuh martabat.
Kehendak menafikan keragaman akan menghancurkan kebesaran dan martabatnya.
Sebab itu, demokrasi yang menyimbolkan kebersamaan dalam keragaman, tidak semestinya menjadi alasan menafikan fitrah keragaman. Biarkan perbedaan berkembang alamiah. Biarkan perbedaan berlangsung penuh keindahan, bak aneka bunga di taman surga. Senyuman tetap dikedepankan, kendati pilihan dan kepentingan berbeda. Situasi inilah yang beberapa hari terakhir ini terasa senyap.
Kedua, kita harus berhati-hati menyangkut urusan politik ini. Tak sedikit contoh, betapa politik bisa menggerus dan memberangus kehidupan bersama yang terajut indah nan damai. Juga tak kurang contoh nyata, betapa politik menjadi momok menakutkan persatuan bangsa. Lebih-lebih politik identitas. Ia cenderung menafikan perbedaan sebagai sunnatullah yang tak terabaikan. Karena itu, kita patut waspada pada penumpung gelap demokrasi, yang berkepentingan mengganggu ukhuwwah wathaniyyah, ukhuwwah basyariyyah dan ukhuwwah insaniyyah bangsa ini.
Persaudaraan yang telah terjalin di kalangan bangsa ini, dibeli dengan harga yang sangat mahal, sehingga dunia menghormati kita. Betapa naifnya, hanya karena perbedaan pilihan politik, kita rela mengorbankan nilai-nilai persaudaraan. Bukankah Islam mengajarkan pada umatnya untuk bersatu dan tidak saling berbecah-belah? (Qs. Ali Imran: 103).
Ketiga, peran stake holder bangsa ini untuk menjaga persaudaraan warganya menjadi lebih urgen. Aparat pemerintah berkewajiban mengayomi mereka dengan kebijakannya. Para tokoh agama berkewajiban menenteramkan jiwa mereka melalui tausiah keagamaannya. Aparat keamanan bertugas menjaga keamanan mereka melalui mandatnya. Dan semua, memiliki tugas menjaga persatuan dan persaudaraan bangsa ini sesuai tupoksi dan porsinya masing-masing.
Selain itu, baik umara (penguasa) maupun ulama (tokoh agama) haruslah senantiasa berkoordinasi dalam segala hal yang terkait kemaslahatan umat. Umara bertugas mengelola kesejahteraan fisik. Ulama bertugas mengelola ketenangan batin dan menjaga moralitas. Berjalan sendiri-sendiri akan menjadikan bangsa ini tidak punya arah dan hanya menunggu waktu kerusakannya. Dalam Hadis Nabi (yang kualitasnya diperselisihkan), dikatakan bahwa dua golongan inilah yang menentukan masa depan umat: jika keduanya baik, umat baik dan jika keduanya rusak, umat rusak.
Untuk itu, mari kita move on bersama menuju kehidupan sosial-politik yang lebih bermartabat. Tempatkan urusan politik di bawah agama, karena agama nilainya lebih tinggi dibanding politik. Dan 01 + 02 = 03, yang bermakna Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.














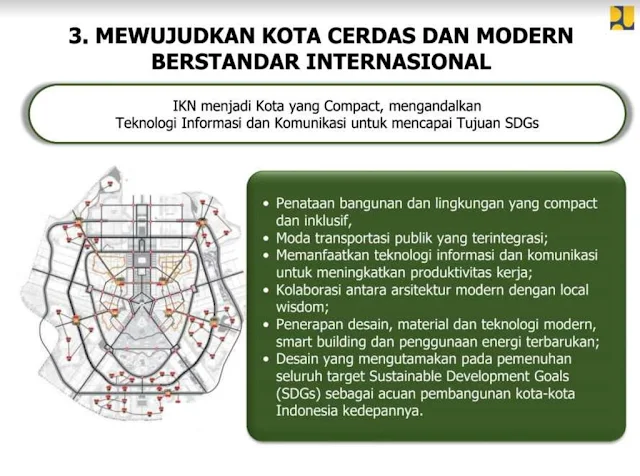

















.jpg)